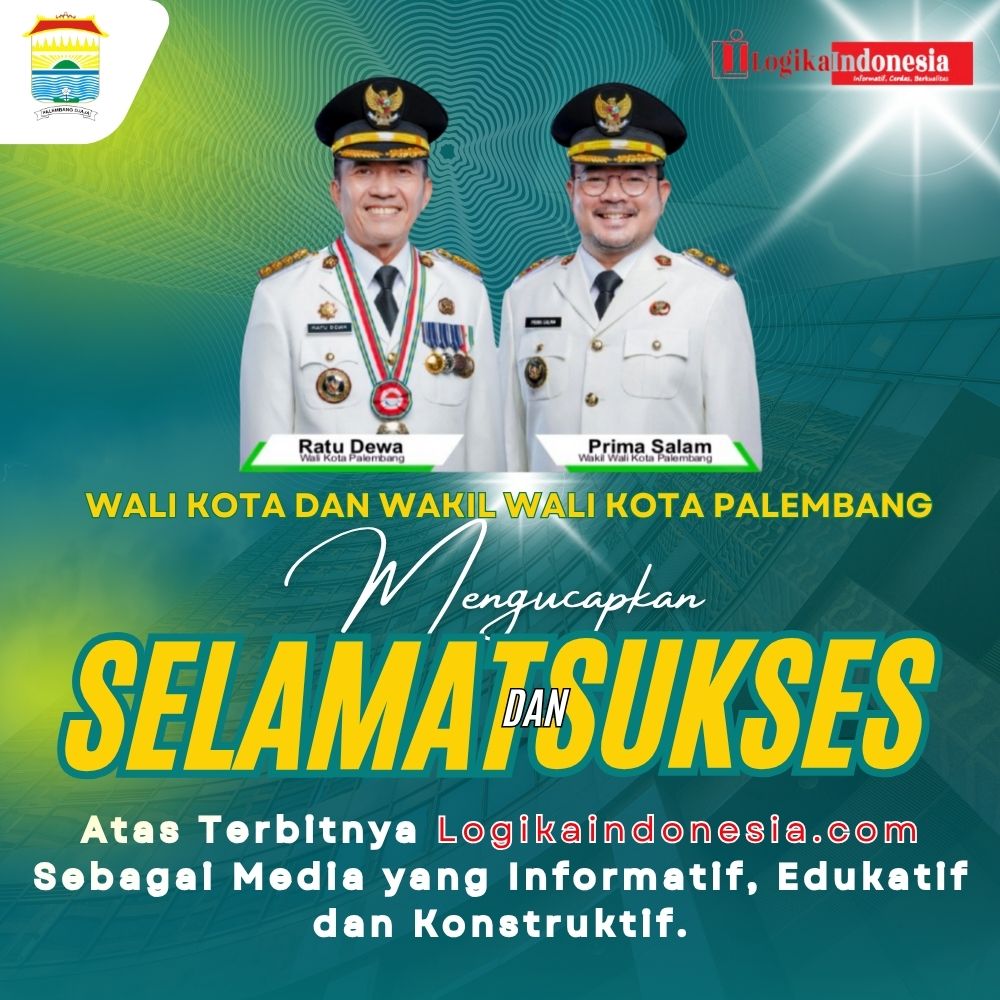Di bawah sorotan lampu kota dan geliat beton yang terus mengembang, ada denyut yang semakin lemah: sungai-sungai Palembang yang dulu menjadi nadi kehidupan, kini sekarat. Diabaikan oleh pemerintah, dilupakan oleh masyarakat, dan tertimbun oleh ambisi pembangunan, ratusan anak Sungai Musi yang dahulu menghidupi kota ini kini tersisa hanya dalam ingatan—dan bahkan itu pun mulai pudar.
Dari Nadi Kehidupan ke Saluran Buangan
Palembang lahir dari air. Sungai Musi dan anak-anaknya bukan sekadar jalur transportasi, melainkan ruang hidup dan lanskap budaya. Sejarawan Unsri, Dr. Dedi Irwanto, mengingatkan bahwa Palembang adalah “kota sungai” dalam arti yang sesungguhnya. Di masa lalu, rumah-rumah menghadap ke sungai, pasar tumbuh di tepian, dan sungai menjadi jalur utama pemerintahan.
Namun kini, sungai justru dimusuhi oleh ruang kota. Modernisasi—dipacu sejak era kolonial—menjadikan sungai sebagai masalah sanitasi yang harus ditundukkan. Pemerintah Gemeente Palembang bahkan mendatangkan ahli Belanda, Rudolf A. van Sandick, hanya untuk mengategorikan sungai… sebelum menutupnya demi pembangunan. Sungai Tengkuruk, yang dulunya jalur diplomatik ke Kraton Cinde Belang, kini menjadi jalan macet tanpa jejak air.
“Transformasi Palembang bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis—dari memuliakan air menjadi meminggirkannya,” kata Dedi.
Urbanisasi yang Menenggelamkan Identitas
Laporan Koalisi Kawali (2025) memperkuat kesaksian para sejarawan: dari lebih dari 700 sungai yang tercatat dalam peta kolonial, hanya 114 yang masih aktif. Sungai berubah menjadi got tertutup, kanal beton, atau saluran limbah. Bahkan proyek restorasi seperti Sekanak Lambidaro, yang menyimpan harapan, dinilai “kosong jiwa” jika tak disertai edukasi dan keterlibatan masyarakat.
Dr. Kemas AR Panji dari UIN Raden Fatah menegaskan, peradaban Palembang adalah peradaban air. Sungai bukan pelengkap kota—ia fondasinya. Benteng Kuto Besak berdiri di antara sungai; syair lisan, pantun, dan ritual adat lahir dari tepian. “Jika sungai hilang, yang tenggelam bukan hanya air, tetapi seluruh narasi budaya kita,” ujarnya.
Regulasi Banyak, Penegakan Nihil
Parahnya, hukum pun seolah tak berdaya. Walau terdapat UU Sumber Daya Air, Perda, dan Perwali, tidak ada penegakan nyata. Pendangkalan, pencemaran, dan pembangunan ilegal terus terjadi. Budayawan Palembang, Hidayatul Fikri, menyerukan pembentukan satgas percepatan normalisasi sungai, pemblokiran sertifikat atas wilayah sungai di BPN, hingga penerbitan Perda larangan membuang sampah.
“Transportasi air harus diaktifkan. Master plan penanganan sungai dan air mesti segera dirancang secara menyeluruh,” tegas mang Dayat sapaan akrab Hidayatul Fikri.
Menyelamatkan sungai adalah menyelamatkan peradaban. Seperti ditegaskan oleh para akademisi, sungai masih bisa menjadi koridor wisata sejarah dan ekonomi hijau. Rumah Limas Cek Mas dan rumah Baba Ong Boen Tjit menjadi saksi bisu kejayaan sungai, dan bisa diangkat sebagai destinasi edukatif dan budaya.
Revitalisasi bukanlah nostalgia. Ia adalah respons ekologis terhadap krisis iklim dan kehancuran kota. Palembang dan kota-kota sungai lainnya harus menata ulang narasinya: dari kota yang menutup airnya menjadi kota yang membuka kembali jalur air dan memori kolektifnya.
“Jika kita gagal menjaga sungai hari ini, kita sedang menenggelamkan peradaban esok hari,” tutup Kemas.