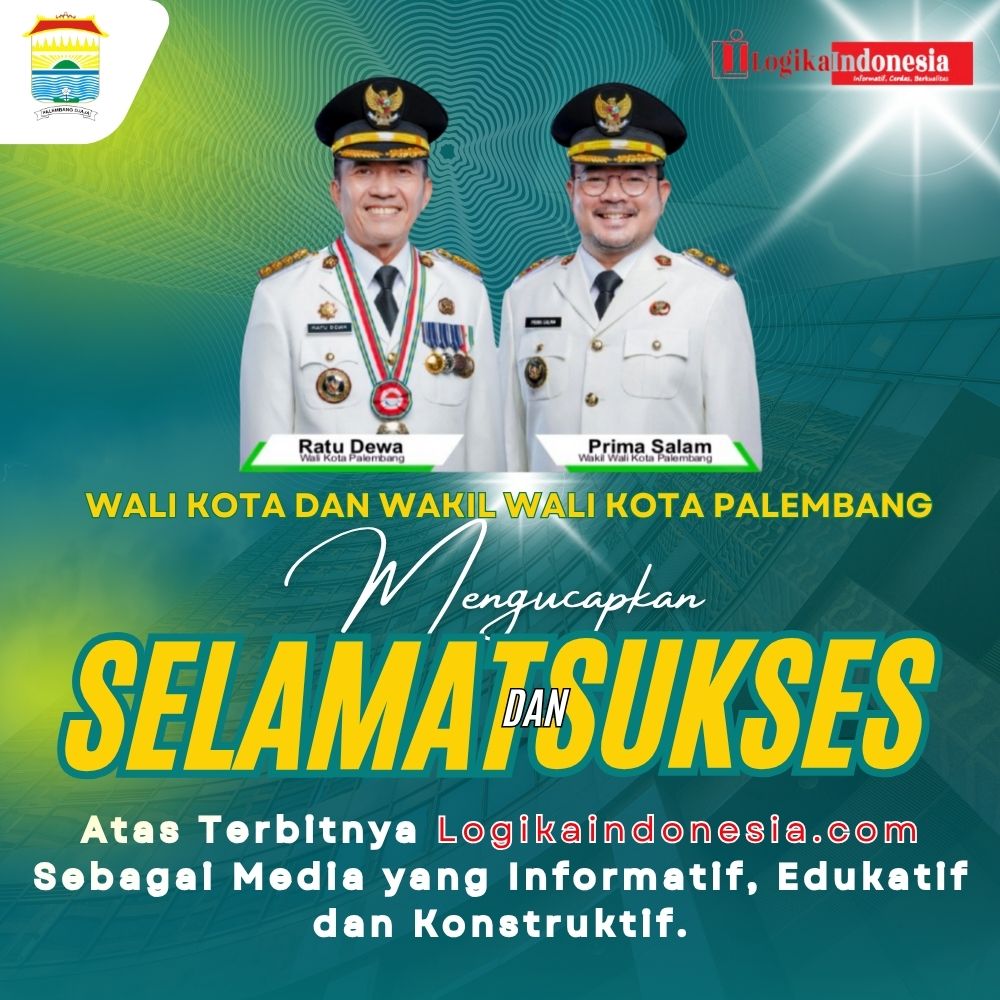Oleh: Ali Goik
Di negeri yang gemar menyanyikan lagu orang lain, pencipta lagu justru kerap menjadi pihak yang paling terlupakan. Mereka mencipta, masyarakat menikmati, negara memungut royalti namun sang pencipta tak mendapat apa-apa. Sistem royalti yang digadang-gadang sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi seniman, justru menyisakan ironi: royalti tetap ditarik, meski penciptanya tak pernah menerima sepeser pun.
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, memiliki kewenangan untuk menarik dan mendistribusikan royalti atas pemakaian lagu di ruang publik. Namun dalam praktiknya, sistem ini hanya menguntungkan mereka yang terdaftar. Lagu yang diputar di restoran, konser, atau media tetap dikenai royalti. Tapi jika penciptanya belum menjadi anggota LMK, royalti itu disimpan selama dua tahun, lalu dialihkan ke dana cadangan.
“Kalau mau dapat hak ekonomi, kamu harus jadi anggota. Undang-undang bilang begitu. Tidak jadi anggota, kamu tidak dapat,” kata Johnny William Maukar, Komisioner LMKN, dalam sebuah wawancara.
Pernyataan itu sah secara hukum, tapi problematis secara etika dan moral. Apakah adil jika lembaga tetap menarik royalti dari karya yang digunakan, sementara penciptanya tidak diberi bagian? Apakah hak ekonomi hanya berlaku bagi mereka yang terdaftar, dan bukan bagi semua pencipta yang karyanya digunakan secara publik?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita menengok ke daerah. Di Sumatera Selatan, banyak pencipta lagu yang aktif menciptakan karya berakar budaya lokal berbahasa daerah, bertema sejarah, atau mengangkat narasi komunitas. Lagu-lagu itu diputar di acara pemerintah, media komunitas, dan ruang publik. Tapi sistem royalti tidak menjangkau mereka. Mereka tidak tahu cara mendaftar, tidak punya akses ke data pemakaian lagu, dan tidak mendapat edukasi tentang hak cipta.
Lebih dari itu, banyak dari mereka tidak melihat sistem royalti sebagai sesuatu yang relevan dengan kehidupan mereka. Mereka mencipta bukan untuk industri, tapi untuk komunitas. Mereka tidak punya label, tidak punya manajer, dan tidak punya koneksi ke pusat-pusat distribusi musik. Tapi karya mereka tetap digunakan sering kali tanpa izin, tanpa kontrak, dan tanpa kompensasi.
Sementara itu, LMKN terus menarik royalti dari pengguna. Dana terkumpul, tapi tidak sampai ke tangan pencipta. Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak ekonomi dan martabat pencipta lagu.
Sistem royalti harus direformasi. Transparansi harus menjadi prinsip utama. Data pemakaian lagu harus dibuka. Dana cadangan harus bisa diklaim dengan mekanisme yang mudah dan terbuka. Pemerintah daerah harus aktif memfasilitasi pendaftaran dan edukasi hak cipta. Dan yang paling penting: pencipta lagu harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Royalti bukan sekadar angka. Ia adalah pengakuan atas kerja kreatif, hak ekonomi, dan keberlanjutan hidup seniman. Jika sistem hanya menguntungkan mereka yang terdaftar, tanpa upaya aktif menjangkau yang terpinggirkan, maka musik hanya jadi komoditas bukan warisan budaya.
Di Sumatera Selatan, kita mengenal lagu-lagu yang lahir dari tepian sungai, dari ritual adat, dari perayaan dan duka. Lagu-lagu itu bukan sekadar hiburan, tapi penanda identitas. Ketika penciptanya tidak diberi hak, kita bukan hanya mengabaikan ekonomi mereka, tapi juga mengabaikan sejarah dan budaya yang mereka wakili.
Jika negara sungguh ingin melindungi pencipta lagu, maka sistem royalti harus berpihak pada mereka yang paling rentan: pencipta independen, musisi daerah, dan seniman komunitas. Tanpa itu, royalti hanya akan menjadi suara sunyi yang tak pernah sampai.
Penulis adalah pencipta lagu, pemerhati musik dan budaya Sumatera Selatan