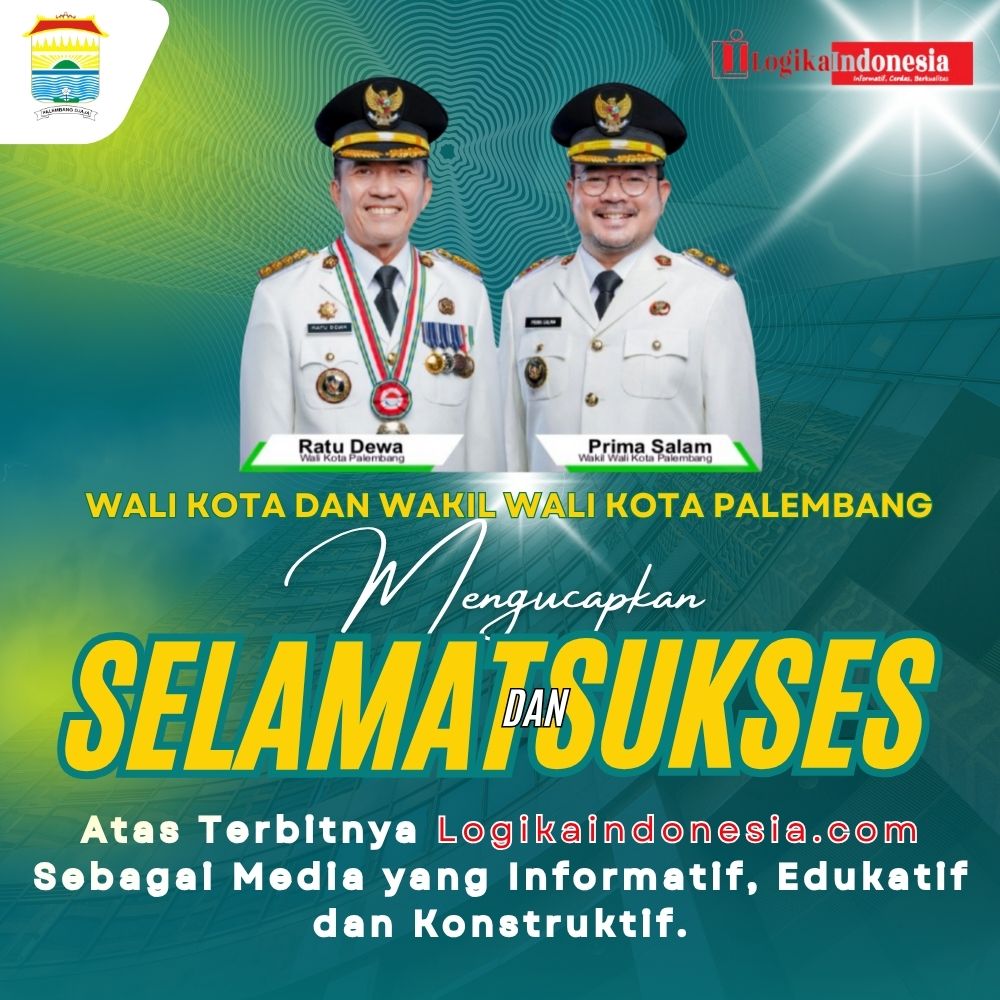Tradisi Sungai Musi yang Digerakkan, Tapi Tak Lagi Dihidupi
PALEMBANG,LogikaIndonesia.Com – Setiap 17 Agustus, Sungai Musi kembali bergemuruh. Perahu Bidar meluncur, tepian sungai dipadati penonton, sorak-sorai menggema, spanduk sponsor berkibar, drone berputar di atas kepala. Pemerintah menyebutnya “pengembalian tradisi.” Tapi bagi sebagian warga tepian, Bidar yang kembali bukanlah Bidar yang mereka kenal.
“Dulu Bidar itu bukan lomba. Itu bagian dari hidup kami,” kata Pak Rasyid, 68 tahun, warga 3–4 Ulu. “Sekarang, semua seragam. Semua panggung. Sungai jadi latar, bukan pusat.”
Pernyataan Pak Rasyid bukan sekadar nostalgia. Ia menyuarakan kegelisahan yang lebih dalam: bahwa tradisi yang dulu hidup sebagai bagian dari keseharian kini berubah menjadi tontonan. Bahwa sungai yang dulu menjadi ruang spiritual dan sosial kini hanya menjadi latar belakang panggung seremonial.

Dari Ritual ke Atraksi
Bidar bukan sekadar perahu panjang dengan pendayung berbaris. Ia adalah warisan Kesultanan Palembang—simbol kekuatan, kerja sama, dan penghormatan terhadap sungai sebagai sumber kehidupan. Dahulu, Bidar digelar dalam momen sakral: Maulid Nabi, sedekah kampung, atau peringatan sejarah lokal. Ia bukan soal kecepatan, tapi soal cerita.
Bidar adalah bagian dari ekosistem budaya sungai. Ia menyatu dengan syair, pantun, dan ritual tepian. Pendayung bukan sekadar atlet, tapi penjaga tradisi. Perahu bukan sekadar alat, tapi simbol kampung dan sejarah.
Namun sejak awal 2000-an, Bidar mulai digeser. Tanggalnya berpindah ke akhir tahun, lalu ke momen pariwisata. Maknanya dikemas ulang: dari ritual menjadi “atraksi budaya.” Pendayung kampung digantikan oleh tim instansi dan perusahaan. Sungai Musi berubah dari ruang spiritual menjadi panggung kompetisi.
“Kalau Bidar hanya jadi lomba, kita kehilangan jantungnya,” kata Darman, pendayung veteran yang pernah mewakili kampungnya dalam Bidar tahun 1980-an. “Yang kita butuhkan bukan hanya perahu, tapi arah.”
Identitas Siapa?
Tahun ini, Bidar digelar tepat pada 17 Agustus. Pemerintah menyebutnya “peneguhan identitas lokal dalam perayaan nasional.” Tapi identitas siapa yang diteguhkan?
Di barisan perahu, nama-nama kampung nyaris tak terlihat. Yang dominan: logo sponsor, instansi, dan jargon promosi. Bahkan, hampir 80 persen perahu yang berlaga berasal dari warga Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir—bukan dari kampung-kampung tepian Musi.
Fenomena Bidar mencerminkan pola yang lebih luas: budaya lokal dijadikan ornamen, bukan narasi. Tradisi diarak, tapi maknanya ditinggalkan. Partisipasi masyarakat dibatasi sebagai penonton, bukan pengarah.
Sungai Sebagai Panggung Utama
Usulan pelaksanaan Bidar pada 17 Agustus bukan keputusan sepihak. Ia lahir dari inisiatif Tim Percepatan Pemajuan Kebudayaan kelompok kerja lintas komunitas, seniman, akademisi, dan tokoh adat yang mendorong pengembalian makna tradisi sungai.
Tim ini mengusulkan tanggal tersebut karena pada hari itu, di lokasi yang sama, biasanya digelar upacara bendera. Bagi mereka, sungai bukan sekadar latar, melainkan ruang utama perayaan kemerdekaan yang berakar pada identitas lokal.
Setelah koordinasi dengan pemerintah kota, Dinas Pariwisata, panitia upacara, dan aparat keamanan, akhirnya disepakati lomba Bidar digelar pada 17 Agustus. Lokasi upacara resmi dipindahkan, memberi ruang bagi sungai untuk kembali menjadi pusat perayaan.
Keputusan ini mencerminkan kompromi antara protokol kenegaraan dan urgensi budaya lokal. Tapi lebih dari itu, ia membuka ruang simbolik bahwa kemerdekaan nasional bisa dirayakan dengan bahasa lokal. Bahwa sungai bisa menjadi panggung utama, bukan latar belakang.
Menuju Kebijakan yang Berakar
Kritik terhadap seremonialisasi Bidar bukan sekadar keluhan. Ia membuka peluang untuk merumuskan kebijakan budaya yang lebih partisipatif. Beberapa usulan konkret yang muncul dari komunitas:
Pertama Penetapan 17 Agustus sebagai tanggal tetap lomba Bidar, menghubungkan kemerdekaan nasional dengan ingatan lokal.
Kedua Program tahunan Bidar dalam kalender budaya kota, lengkap dengan anggaran dan dukungan teknis.
Ketiga Fasilitasi kecamatan untuk membuat perahu tradisional, melibatkan pengrajin lokal dan komunitas pemuda.
Keempat berikan Ruang partisipatif bagi pendayung veteran, seniman lokal, dan warga tepian sebagai pengarah acara.
“Kalau kita hanya bicara soal lomba, kita kehilangan sungai sebagai ruang hidup,” ujar Nuraini, seniman visual yang aktif dalam kampanye budaya sungai. “Kita perlu mengembalikan narasi, bukan sekadar perahu.”
Tradisi yang Belum Pulang
Tanpa langkah ini, Bidar akan terus melaju—cepat, meriah, dan kosong. Tapi jika kita berani mengembalikan makna, Bidar bisa menjadi perahu yang membawa kita pulang: ke sungai, ke sejarah, dan ke jantung budaya kita sendiri.
Pertanyaannya kini bukan lagi soal tanggal atau teknis pelaksanaan. Tapi soal keberanian untuk menjadikan budaya sebagai ruang hidup, bukan sekadar panggung. Apakah kita siap mendengarkan suara sungai, bukan hanya gemuruh lomba?