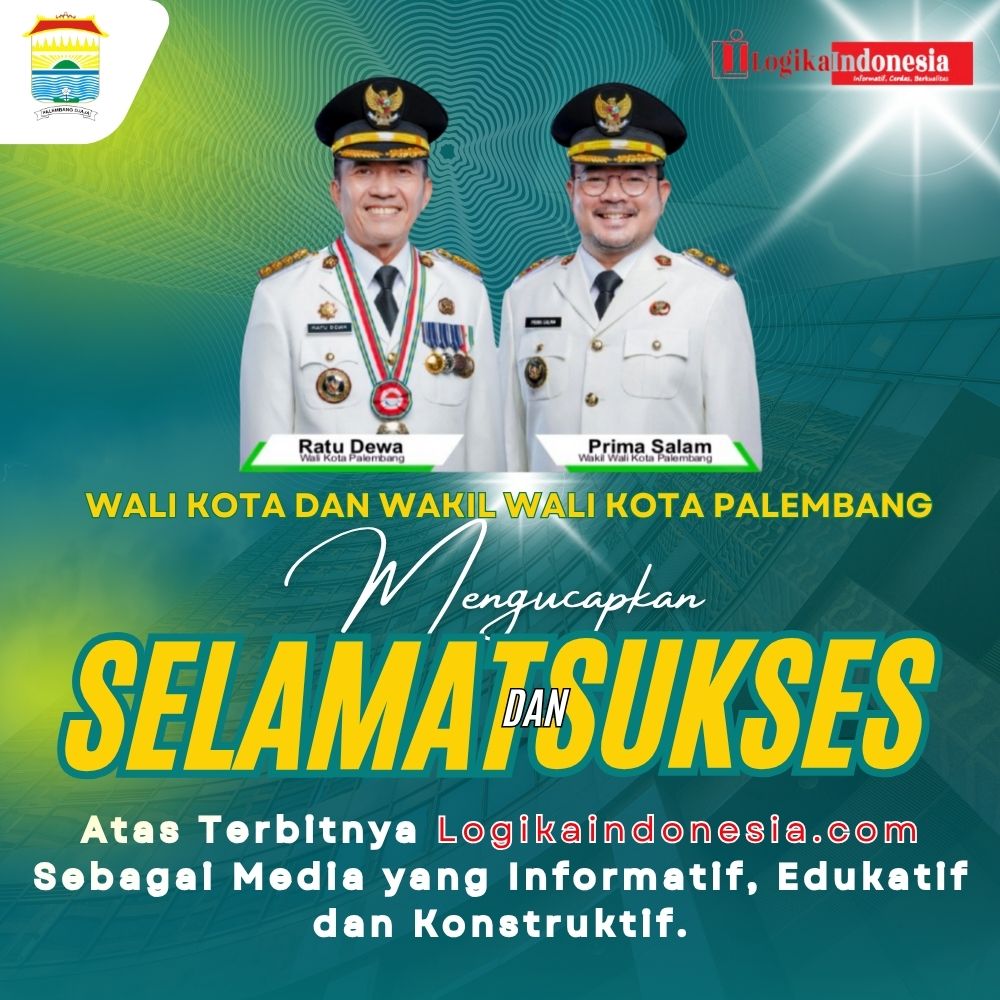Oleh: Vebri Al-Lintani
KISAH RATU SINUHUN masih banyak menyimpan rahasia namun selalu menarik diperbincangkan. Namanya selalu dikaitkan dengan prakarsa intelektualnya, yakni: Undang-undang Simbur Cahaya yang berlaku di uluan Batanghari Sembilan (uluan Negeri Palembang yang wilayahnya sebagian besar termasuk dalam Sumatera bagian selatan, yakni: Sumatera Selatan, sebagian Lampung, sebagian Jambi dan Bengkulu).
Pada bagian awal (Bab Satu) Undang-undang Simbur Cahaya memuat aturan sopan santun pergaulan bujang gadis dan perlindungan perempuan dengan penerapan sanksi adat bagi siapa saja yang melecehkan perempuan. Oeh karena itu pula, Ratu Sinuhun disebut sebagai tokoh feminisme dari Palembang Darussalam. Sejatinya, Undang-Undang Simbur Cahaya tidak hanya memuat tentang perlindungan bagi perempuan tetapi juga tentang berbagai macam aturan seperti adat perhukuman, adat marga, adat kaum, dan adat dusun dan berladang.
Bagi masyarakat uluan negeri Palembang Darussalam, keterkenalan Ratu Sinuhun melebihi suaminya, Pangeran Sido Ing Kenayan, Raja Palembang yang berkuasa pada 1636-1642 M. Menurut catatan orang-orang Belanda yang dikutip oleh Dudy Oskandar (Berita Pagi, 28/10/2019) dari buku “Hidup Bersaudara -Sumatra Tenggara pada Abad XVII dan XVIII, karya Barbara Watson Andaya, terbitan Ombak Yogyakarta, 2016”), ketokohan Ratu Sinuhun dapat dilihat dari perannya yang sangat menonjol dan karya yang monumental. Dalam naskah yang lain, sosok penting ini dikatakan juga memberikan perintah menanam lada dan aturan-aturan lain yang kemudian disebut sebagai Piagem (piagam) Ratu Sinuhun. Dalam piagam tersebut, tiada disebutkan nama suaminya Pangeran Sido Ing Kenayan, melainkan hanya nama Ratu Sinuhun.
Satu piagam yang terbuat dari lempeng tembaga ditemukan oleh peneliti Van Dongen, ketika berkunjung di komunitas Suku Kubu di area Sei Lalan, lokasi Sei Bahar Musi Banyuasin di Sumatera Selatan. Diperkirakan, piagam itu berasal dari masa Kerajaan Palembang abad ke-17 yang dipimpin oleh Ratu Sinuhun. Umumnya, piagam seperti itu diberikan kepada suku-suku di wilayah negeri Palembang, terutama suku-suku yang terletak di daerah Sindang Merdeka atau daerah yang “merdeka” dan tidak dibebankan membayar pajak kepada Kerajaan Palembang.
Pada wilayah sindang merdika lainnya, yaitu Sukubangsa Besemah, nama Ratu Sinuhun dikenal sebagai orang yang berjasa dan dihormati karena telah menjadikan Undang-undang Simbur Cahaya sebagai aturan negeri Palembang. Sebelumnya, sukubangsa Besemah telah mengenal sistem adat Lampik Empat Merdike Due dengan materi norma yang diatur dalam aturan adat yang substansinya dipakai dalam Simbur Cahaya. Jadi, mereka menganggap bahwa Simbur Cahaya adalah undang-undang yang berasal dari Besemah yang dilegitimasi oleh penguasa Palembang. Memang, dalam beberapa pendapat menyebutkan bahwa Simbur Cahaya diambil dari norma-norma adat yang ada di suku-suku uluan negeri Palembang.
Disamping itu, dalam naskah Jago-Kersah, een Orang-toea (oudste) in de doeson (dorp) Poelau Pangong, sebenarnya telah muncul nama Puteri Selimbur Caye. Nama ini muncul dalam kisah seorang tokoh wali tua dari Majapahit yang datang ke Palembang. Ketika tiba di Sungai Musi dia memancing di kaki Bukit Seguntang. Pancing terkait dengan gadis bernama Putri Selimbur Cahaya, anak seekor naga, kemudian dinikahi dan mendapat dua orang anak. Anak sulung laki-laki bernama Yang Dipertuan Sakti, merantau ke Pagaruyung, Minangkabau. Anak Bungsu perempuan bernama Putri Sindang Biduk menikah dengan anak penguasa Bukit Seguntang, Iskandar Zulkarnain (Segentar Alam), bernama Patih. Yang Pertuan Sakti memiliki tiga anak yakni Tuan Mincang, Tuan Barisan dan Tuan Atung Bungsu. Atung Bungsu merantau kembali ke Palembang, masuk ke ulu pedalaman, di Benua Keling, tanah Pasemah (dikutip dari artikel ”Historiografi dan Identitas Ulu di Sumatera Selatan”, Mozaik Humaniora Vol. 18 (2): 157-166 © Dedi Irwanto, Bambang Purwanto, Djoko Suryo (2018) “). Naskah ini menegaskan tentang nama Puteri Selimbur Caye dan kekerabatan antara Besemah dan Palembang.
Selain itu, dalam “Hidup Bersaudara -Sumatra Tenggara pada Abad XVII dan XVIII”, Ratu Sinuhun juga dikaitkan dengan perkampungan iliran, karena ketika ada orang-orang melakukan tindakan kriminal atau menolak para utusan Ratu Sinuhun, mereka akan dibawa paksa ke ibu kota ilir (Palembang) dan diberi sebuah pilihan apakah mereka ingin menetap di sana atau ingin dihukum. Menurut salah satu pegawai Belanda pada tahun 1823, penduduk ketika itu biasanya lebih memilih menetap daripada dihukum. lnilah alasan mengapa para penduduk hilir langsung berada di bawah kendali Pemimpin di ibu kota dan lebih bertanggungjawab untuk mengabdi daripada para penduduk di dataran tinggi.
Pada bagian lain dalam buku ini juga dikatakan bahwa, Ratu Sinuhunlah yang menyusun peringkat para bangsawan dengan membagikan gelar dan Ratu Sinuhun pula yang pertama kali memberikan timbangan bagi para pedagang. Selain itu, selama masa kekuasaannya, untuk pertama kalinya aturan dibuat untuk mengatur para penduduk di pedalaman, bahkan para penghuni hutan (orang Kubu) berkata, bahwa Ratu Sinuhun adalah orang pertama yang memberi mereka pakaian, mengajari mereka bagaimana cara untuk memakan nasi dan menggunakan garam, dan membuat mereka menjadi kawulanya.
Meninjau tindak tanduk Ratu Siuhun yang luar biasa dan keberlakuan Simbur Cahaya sebagai aturan adat yang efektif hingga sebelum dibubarkannya sistem Marga di Sumatera Selatan pada tahun 1983, maka akan sangat wajar jika Ratu Sinuhun ramai diperbincangkan. Namun kisah kemampuan dan integritas Ratu Sinuhun tidak sebanding dengan data-data pribadinya. Masih banyak pertanyaan tentang Ratu Sinuhun yang perlu ditelusuri, misalnya, apakah Ratu Sinuhun adalah sebutan gelar atau nama asli. Jika sebutan gelar siapakah nama aslinya. Lalu kapan Ratu Sinuhun dilahirkan, bagaimana pendidikannya dan lain sebagainya.
Dalam tulisan orang Belanda disebutkan, bahwa Ratu Sinuhun adalah sebutan “simbol” kekuasaan Palembang. Bisa jadi, Ratu Sinuhun lebih dari satu orang dan mungkin juga dia bukan sebagai seorang perempuan. Dalam istilah orang Besemah, dikenal dengan istilah “keratuan” untuk menyebut “kerajaan”. Raja pun disebut dengan Ratu. Ratu Sinuhun seringkali disebut sebagai simboI dari semua yang baik pada diri seorang penguasa.
Ketika para penduduk bumiputra ditanya tentang suami Ratu Sinuhun, jawaban mereka begitu samar. Kebanyakan berkata bahwa Ratu Sinuhun kawin dengan Pangeran Sido Ing Kenayan yang dikatakan pernah berkuasa pada awal abad XVII walaupun penduduk yang lain berkata bahwa Ratu Sinuhun merupakan rekan hidup dan istri dari Sultan Abdurrahman.
Selain itu, di daerah uluan juga mengenal istilah “sunan” (kependekan susuhunan atau suhunan) sebagai raja Palembang Darussalam. Jarang sekali penduduk uluan menyebut Sultan Palembang. Hal ini terkait dengan pamor pendiri Kesutanan Palembang Darussalam, Sunan Abdulrachman Khalifatul Mukminin Syaidul Imam yang terkenal sebagai Cinde Balang (Walang) yang bermakam dekat sebuah candi yang bernama Cinde Walang. Sunan Cinde Walang diyakinin memiliki kekuatan supranatural (sakti) dan cakap dalam berperang. Dikatakan (masih dalam tulisan Belanda yang dikutip Dudy), bahwa ”bahwa ia dicintai dan dihormati oleh para kawulanya. Beliau bertabiat tenang, adil dan bijaksana, dan dibawah kepemimpinannya negeri tumbuh subur dan makmur”.
Tafsir terhadap istilah “Ratu Sinuhun” yang bermakna junjungan atau penguasa di Palembang sebagaimana istilah “Sunan” membuat keraguan bagi yang menganggap Ratu Sinuhun adalah gelar seorang Ratu. Artinya, pada pendapat ini menganggap Ratu Sinuhun belum tentu seorang perempuan isteri dari Sido Ing Kenayan. Namun bagi penulis, dengan menimbang berbagai data yang ada (meski belum memadai) masih beryakinan bahwa Ratu Sinuhun adalah isteri dari Raja Palembang yang disebut dengan Sido Ing Kenayan. Bukankah istilah Sunan juga berasal dari gelar pemimpin Palembang sehingga diingat oleh masyarakat uluan.
Ratu Sinuhun diperkirakan lahir di Palembang pada sekitar akhir abad ke-16, dan wafat pada tahun 1642 M. Ayahnya bernama Maulana Fadlallah, yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Manconegara Caribon. Di dalam catatan sejarah, Pangeran Manconegara merupakan cikal bakal lahirnya Dinasti Cirebon di Kesultanan Palembang. Sebagaimana diketahui Kesultanan Palembang Darussalam didirikan oleh Sultan Abdurrahman (Ki Mas Hindi) bin Pangeran Muhammad Ali Seda ing Pasarean bin Pangeran Manconegara Caribon (sumber : Ratu Sinuhun (wikipedia)).
Ada yang berpendapat bahwa garis Nasab Ratu Sinuhun jika dirunut ke atas akan sampai ke Rosullulah Muhammad SAW. Beginilah nasab Ratu Sinuhun tersebut: Ratu Sinuhun binti Maulana Fadlallah Pangeran Manconegara Caribon bin Maulana Abdullah Pangeran Adipati Sumedang Negara bin Maulana Ali Mahmud Nuruddin Pangeran Wiro Kusumo] bin Sunan Giri II atau Sunan Dalem bin Sunan Giri atau Maulana Muhammad Ainul Yaqin bin Maulana Ishaq bin Syaikh Ibrahim Zain al Akbar bin Syaikh Jamaluddin Husain Akbar bin Syaikh Ahmadsyah Jalal bin Syaikh Abdullah Azmatkhan bin Syaikh Abdul Malik al Muhajir bin Syaikh Alawi Ammil Faqih bin Syaikh Muhammad Shohib Mirbath bin Syaikh Ali Khali’ Qasam bin Syaikh ‘Alwi Shohib Baiti Jubair bin Syaikh Muhammad Maula Ash-Shaouma’ah bin Syaikh ‘Alwi al-Mubtakir bin Syaikh ‘Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir bin Syaikh ‘Isa An-Naqib bin Syaikh Muhammad An-Naqib bin Imam ‘Ali Al-’Uraidhi] bin Imam Ja’far Ash-Shadiq bin Imam Muhammad al-Baqir bin Imam ‘Ali Zainal ‘Abidin bin Imam Husain Asy-Syahid bin Fathimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah.
Sementara dari pihak Ibu, Ratu Sinuhun adalah putri dari Nyai Gede Pembayun binti Ki Gede ing Suro Mudo. Beliau merupakan sepupu suaminya (Pangeran Sido ing Kenayan), yang merupakan putra dari Ki Mas Adipati Angsoko bin Ki Gede ing Suro Mudo/Ki Mas Anom Adipati Jamaluddin (sumber : Sejarah Kesultanan Palembang).
Ratu Sinuhun bersemayam di Sabo ing Kingking (Sabokingking).
Kehidupan Ratu Sinuhun berakhir dengan tragedi yang menyedihkan. Berdasarkan cerita lisan, dia dan suaminya terbunuh oleh panglima kerajaan yang bernama Jaladeri. Peristiwa tersebut berpangkal pada kesalahpahaman antara Jaladeri dan Raja Sido Ing Kenayan. Dikisahkan, Jaladeri baru saja beisteri yang kedua atas permintaan isteri pertamanya. Namun setelah menikah, isteri kedua tersebut diminta raja menginap di Istana Kuto Gawang. Ketika pulang ke rumah, isteri pertama meminta agar Jaladeri menjemput kembali isteri mudanya tersebut. Barangkali karena percekcokan mulut antara Raja dan Jaladeri maka terjadilah peritiwa penikaman oleh Jaladeri yang menewaskan Raja dan Ratu Sinuhun. Amukan Jaladeri kemudian dihentikan Ki Bodrowongso (Panglima bawah manggis), salah seorang pembesar kerajaan Palembang yang berasal dari Demak, sehingga Jaladeri menyusul tewas. Ratu Sinuhun dikabarkan tidak meninggalkan keturunan.
Oleh karena suami Ratu Sinuhun meninggal dengan cara dianiaya maka dia mendapat julukan (aranan) Sido Ing Kenayan, artinya mati karena dianaya. Mereka berdua dimakamkan di kawasan 1 Ilir yang terkenal dengan nama Sabo Ing Kingking atau Sabo Kingking yang artinya tempat (sabo) bersedih (kingking).
Demikian sekias kisah Ratu Sinuhun. Lebih kurang penulis minta maap. Wallahualam bisawab.